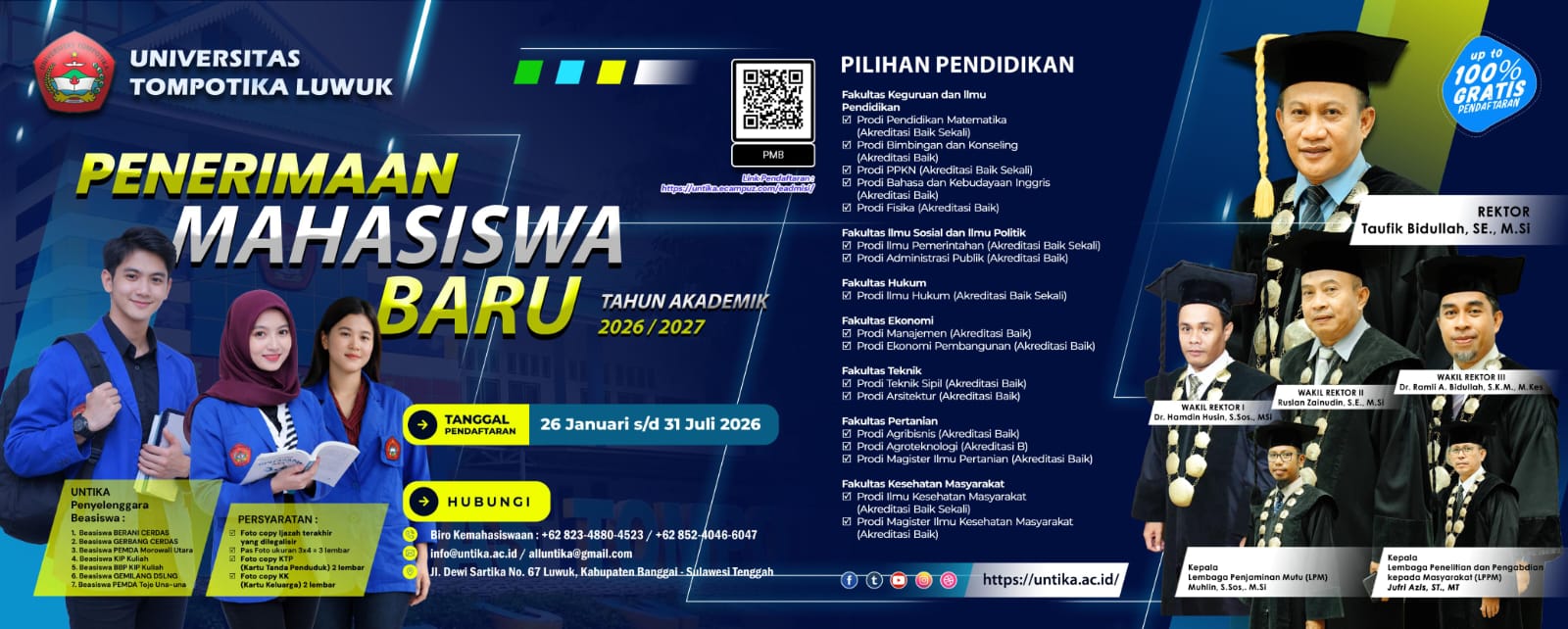Oleh: Suryani M. Sy. Zubair, SE
Beberapa konten kreator dan influencer yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pascabencana di Sumatra tidak hanya menghadapi perdebatan wajar di ruang publik digital, tetapi justru menjadi sasaran teror dan intimidasi yang serius serta sistematis. Serangan yang mereka alami melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk ke wilayah kekerasan nyata, mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, hingga peretasan akun pribadi. Bentuk-bentuk intimidasi ini menunjukkan eskalasi yang berbahaya, di mana kritik kebijakan dibalas dengan upaya menebar rasa takut.
Rentetan peristiwa yang terjadi mencerminkan pola teror yang terencana. Rumah salah satu kreator dilaporkan dilempari bom molotov, fasilitas pribadi influencer dirusak dengan coretan dan lemparan telur busuk, serta pesan ancaman disertai bangkai ayam yang ditinggalkan di kediaman seorang aktivis yang vokal mengkritik respons pemerintah terhadap bencana (Media Indonesia, 31/12/2025). Tindakan-tindakan ini bukan sekadar ekspresi kemarahan individu, melainkan bentuk intimidasi simbolik dan fisik yang bertujuan membungkam suara kritis melalui ketakutan.
Teror dan intimidasi terhadap aktivis serta influencer yang bersikap kritis merupakan manifestasi kekerasan negara yang bersifat struktural. Kekerasan ini tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan represif yang terang-terangan oleh aparat, tetapi bekerja melalui pembiaran, normalisasi, dan iklim impunitas yang memungkinkan teror terhadap suara kritis terus berlangsung. Sasaran utamanya bukan hanya individu yang dikritik, melainkan ruang publik itu sendiri. Dengan menciptakan efek gentar (chilling effect), negara—secara langsung atau tidak—mendorong masyarakat luas untuk memilih diam, menarik diri dari diskursus publik, dan menghindari kritik demi keselamatan pribadi.
Ketika kritik kebijakan dibalas dengan teror, negara sedang menggeser mekanisme demokrasi dari dialog dan akuntabilitas menuju represi dan pembungkaman. Dalam kondisi semacam ini, kritik tidak lagi dipandang sebagai bagian sah dari kontrol rakyat terhadap kekuasaan, melainkan direduksi sebagai ancaman yang harus dieliminasi. Akibatnya, demokrasi kehilangan substansinya dan berubah menjadi sekadar prosedur formal: pemilu tetap ada, institusi tetap berjalan, tetapi kebebasan sipil, ruang oposisi, dan hak berekspresi dikekang secara sistematis. Inilah ciri dari demokrasi otoriter—sebuah sistem yang tampak demokratis di permukaan, namun otoriter dalam praktiknya.
Lebih jauh, praktik intimidasi terhadap suara kritis mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan sekaligus pelemahan supremasi hukum. Ketika teror terhadap pengkritik tidak diusut secara transparan dan tuntas, hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung warga negara dan justru berubah menjadi alat kekuasaan. Kritik yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen koreksi kebijakan diperlakukan sebagai kejahatan, sementara kegagalan kebijakan dan kelalaian negara dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Dalam situasi ini, prinsip kedaulatan rakyat dikhianati, ruang partisipasi publik ditutup, dan impunitas terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat semakin menguat.
Teror sengaja diproduksi untuk menciptakan rasa takut kolektif terhadap rezim yang berkuasa. Ketakutan ini berfungsi sebagai alat kontrol politik agar stabilitas kekuasaan terjaga bukan melalui kepercayaan rakyat, transparansi, dan keadilan, melainkan melalui represi dan intimidasi. Rakyat didorong untuk patuh bukan karena yakin, tetapi karena takut. Rezim yang anti kritik dengan demikian menunjukkan watak kekuasaan yang rapuh: tidak mampu menghadapi koreksi, alergi terhadap perbedaan pendapat, dan bergantung pada kekerasan simbolik maupun nyata untuk mempertahankan legitimasi.
Dalam konteks ini, teror dan intimidasi terhadap aktivis serta influencer kritis harus dipahami sebagai bagian dari pola kekerasan negara yang terstruktur dan sistemik. Praktik semacam ini tidak hanya melumpuhkan partisipasi publik, tetapi juga menormalisasi represi sebagai instrumen pemerintahan. Ketika kritik diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai mekanisme koreksi, negara sedang bergerak menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat dan semakin mengokohkan watak kekuasaan yang otoriter di balik wajah demokrasi.
Dalam Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, praktik intimidasi dan teror terhadap rakyat bertentangan secara mendasar dengan konsep kepemimpinan. Islam memandang penguasa sebagai junnah atau perisai dan pelindung bagi rakyat, bukan sebagai sumber ancaman dan ketakutan. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa imam (pemimpin) adalah junnah, yang melindungi rakyatnya dari kezaliman dan bahaya, serta menjaga hak-hak mereka, bukan menebar teror untuk mempertahankan kekuasaan.
Hubungan antara penguasa dan rakyat dalam Islam diikat oleh syariat, bukan oleh kehendak kekuasaan. Penguasa berkewajiban menjalankan amanah sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung), sementara rakyat memiliki hak dan kewajiban melakukan muhasabah lil hukam—mengoreksi, menasihati, dan mengkritik penguasa ketika menyimpang dari keadilan dan kebenaran. Kritik dalam Islam bukan tindakan subversif, melainkan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar yang dijamin, dimuliakan, dan bahkan diperintahkan.
Sejarah pemerintahan Islam memberikan teladan yang jelas. Para khalifah (kepala negara) justru membuka ruang kritik, bahkan di hadapan publik. Amirul mukminin Umar bin Khattab ra. dikoreksi secara terbuka oleh rakyatnya dan menerima kritik tersebut dengan lapang dada, tanpa intimidasi atau pembalasan. Kritik dipandang sebagai penjaga keadilan dan pengingat amanah, bukan ancaman bagi legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, teror terhadap suara kritis bukan hanya pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi modern, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam yang menjunjung keadilan, perlindungan rakyat, dan kebebasan menyampaikan kebenaran.
Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb. (*)