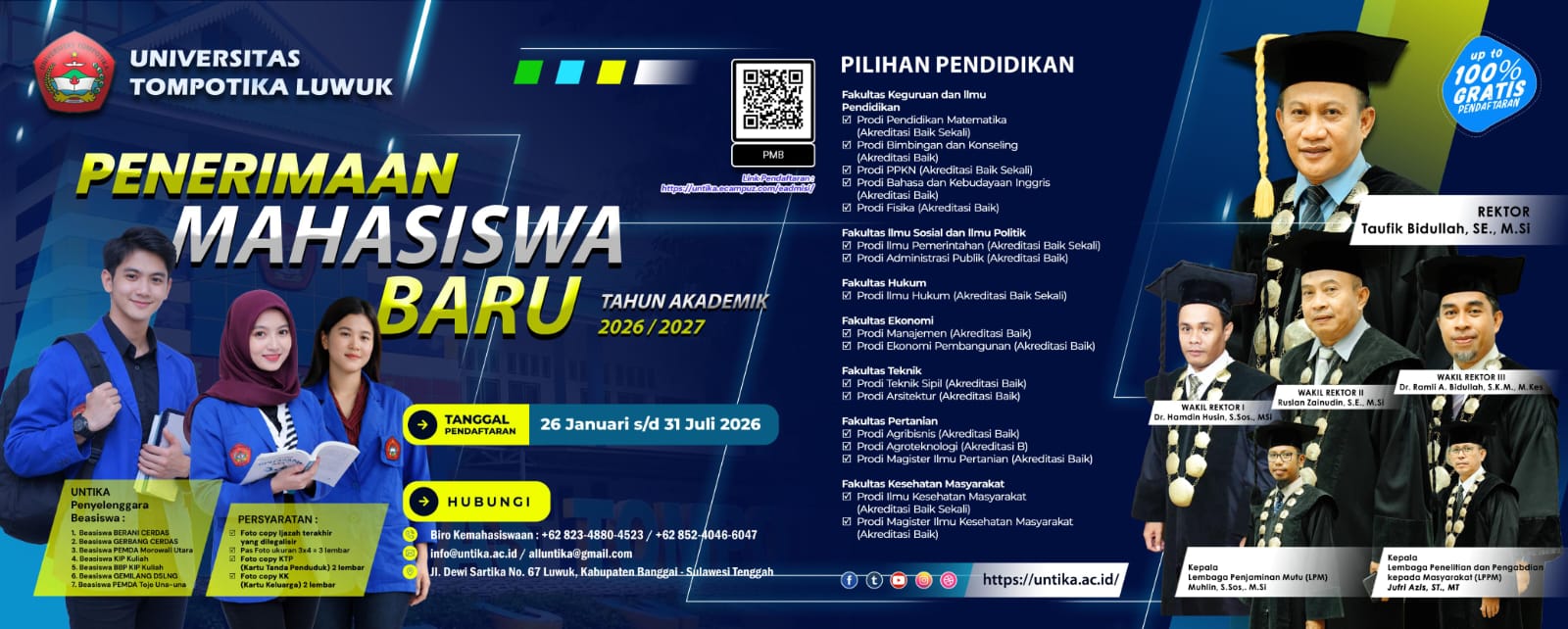Oleh: Risno Mina SH., MH., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk)
Sengketa tanah di Tanjung Sari bukan sekadar perkara perdata biasa, melainkan potret nyata problem struktural penegakan hukum pertanahan di Indonesia. Meski secara formal telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht), kasus ini justru menyisakan ketidakpastian hukum dan luka sosial yang mendalam bagi masyarakat.
Dalam konteks negara hukum, kondisi tersebut patut dikritisi secara objektif, karena hukum tidak hanya dituntut final, tetapi juga adil dan dapat dilaksanakan secara benar.
Merujuk pada penelitian Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, dan Hardianto Djanggih dalam Jurnal Law Reform (2018), sengketa tanah Tanjung Sari memperlihatkan adanya persoalan mendasar pada tahap penentuan objek sengketa dan pelaksanaan eksekusi putusan.
Penulis menegaskan bahwa sejak awal, objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk secara konsisten hanya meliputi dua bidang tanah dengan ukuran dan batas tertentu. Fakta ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang bersifat deklaratoir atas kepemilikan dua bidang tanah tersebut
Namun persoalan mulai muncul ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 2351 K/Pdt/1997 menggunakan deskripsi batas wilayah yang lebih luas, merujuk pada hamparan tanah ±6 hektare sebagai riwayat penguasaan tanah Penggugat Intervensi.
Dalam perspektif hukum acara perdata, deskripsi tersebut seharusnya dibaca sebagai argumentasi pembuktian, bukan sebagai perluasan objek sengketa yang dapat dieksekusi. Di sinilah letak persoalan tafsir hukum yang krusial.
Menurut kaidah hukum acara perdata, hakim terikat pada asas ne ultra petita partium, yaitu larangan menjatuhkan putusan melebihi apa yang dimohonkan. Ketika eksekusi justru dilakukan terhadap lahan hingga ±18 hektare dan berdampak pada ratusan kepala keluarga yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara, maka tindakan tersebut patut dinilai sebagai penyimpangan eksekusi. Pendapat ini sejalan dengan analisis Nasrun Hipan dkk. (2018) yang menegaskan bahwa eksekusi demikian tidak sejalan dengan amar condemnatoir putusan Mahkamah Agung, yang secara limitatif hanya menghukum para Tergugat Intervensi untuk mengosongkan objek sengketa tertentu.
Lebih jauh, pelaksanaan eksekusi yang menyasar tanah-tanah bersertifikat hak milik milik warga yang tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan mana pun, jelas bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 3283 K/Pdt/1994.
Yurisprudensi tersebut secara tegas menyatakan bahwa selama sertifikat hak milik tidak dibatalkan, maka objek tersebut tidak dapat dieksekusi. Dengan demikian, eksekusi di Tanjung Sari bukan hanya problem administratif, melainkan persoalan serius dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.
Dimensi sosial dari sengketa ini tidak dapat diabaikan. Eksekusi yang berujung pada pembongkaran ratusan rumah dan peminggiran warga dari ruang hidupnya telah menciptakan trauma kolektif dan rasa ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.
Dalam konteks ini, hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), dan justru berubah menjadi sumber ketakutan. Padahal, tujuan utama hukum pertanahan sebagaimana diamanatkan UUPA adalah menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pandangan kritis juga disuarakan dalam artikel media Suara Transformasi (9 Januari 2026) yang memuat pendapat praktisi hukum Nasrun Hipan yang juga sebagai akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk. Ia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan hingga merugikan warga yang tidak pernah berperkara. Menurutnya, objek eksekusi harus dibaca secara ketat sesuai amar putusan, bukan berdasarkan asumsi historis penguasaan tanah. Kesalahan tafsir tersebut berpotensi menciptakan konflik horizontal baru dan memperpanjang penderitaan masyarakat Tanjung Sari.
Dari sudut pandang hukum progresif, kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari rasa keadilan masyarakat. Putusan yang inkracht memang harus dihormati, tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Negara, melalui pengadilan, tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa banyak warga Tanjung Sari menguasai tanah berdasarkan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh negara sendiri. Ketika negara mengabaikan sertifikat tersebut dalam eksekusi, maka negara sesungguhnya sedang mengingkari tindakannya sendiri.
Oleh karena itu, tulisan ini menegaskan bahwa sengketa tanah Tanjung Sari belum selesai secara substantif. Penyelesaian yang hanya bertumpu pada legalitas formal tanpa keadilan sosial justru memperdalam konflik.
Diperlukan langkah korektif berupa evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan eksekusi, perlindungan hukum bagi warga terdampak, serta pembacaan ulang putusan secara kontekstual dan bertanggung jawab. Hukum seharusnya hadir sebagai solusi, bukan sebagai momok yang terus menghantui kehidupan masyarakat Tanjung Sari. (*)