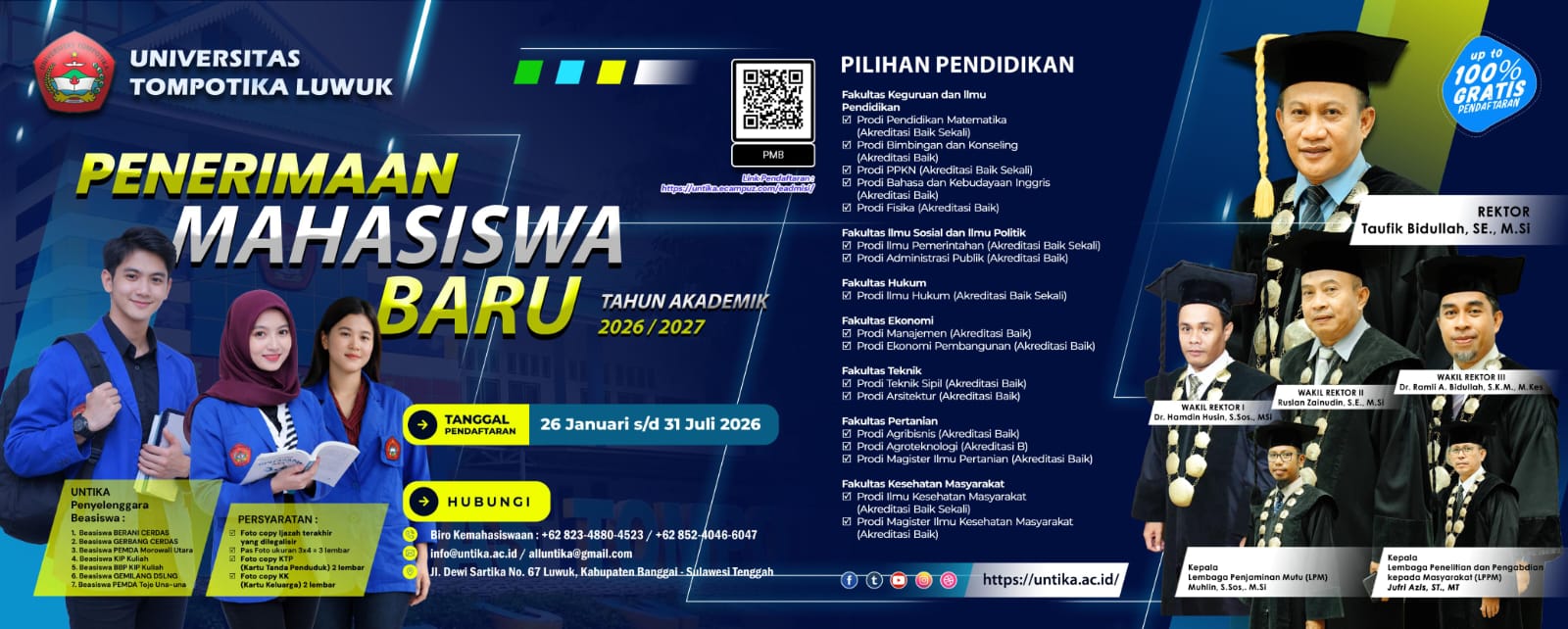Oleh: Suryani M. Sy. Zubair, SE
Bencana longsor dan banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan beberapa daerah lain. Hujan berintensitas tinggi selama beberapa hari menyebabkan debit air sungai meningkat drastis dan memicu pergerakan tanah di berbagai titik rawan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, angkat suara terkait belum ditetapkannya status bencana nasional atas banjir dan longsor tersebut. “Untuk status bencana nasional sementara ini belum, setahu saya. Tetapi perlakuannya sudah nasional dari hari pertama,” ujarnya, Senin (1/12/2025) seperti dikutip dari KompasTV.
Adapun jumlah korban meninggal dunia per Senin sore (1/12) tercatat mencapai 604 orang. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut data tersebut merupakan pembaruan terbaru. (CNN Indonesia, 1/12/2025)
Bencana kali ini tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan ekstrem, tetapi diperparah oleh menurunnya daya tampung dan daya resap wilayah. Ketika lingkungan kehilangan kemampuan alaminya, hujan ekstrem yang semestinya dapat diserap justru berakhir sebagai ancaman.
Analisis: Bencana yang Lahir dari Kerusakan Sistemik
Bencana yang berulang bukan sekadar fenomena alam atau ujian kehidupan. Ia adalah akumulasi kejahatan ekologis yang berlangsung lama, sistematis, dan ironisnya sering dilegitimasi oleh kebijakan penguasa. Kombinasi eksploitasi berlebihan dan lemahnya pengawasan telah merusak keseimbangan ekologis di banyak wilayah.
Pemberian konsesi lahan dalam jumlah besar kepada korporasi membuka pintu eksploitasi masif tanpa kendali. Hutan—yang berfungsi sebagai benteng alami pencegah bencana—ditebangi dan digantikan oleh aktivitas ekonomi jangka pendek. Pemerintah terlalu mudah mengeluarkan izin, mulai dari sawit, tambang terbuka, hingga tambang yang dikelola lembaga tertentu termasuk ormas. Kerusakan pun tak terbendung.
Regulasi yang mestinya melindungi lingkungan sering justru memperluas ruang eksploitasi. UU Minerba dan UU Cipta Kerja, misalnya, dianggap banyak pemerhati lingkungan sebagai produk hukum yang mempermudah investasi tanpa memperhatikan daya dukung alam. Aturan-aturan ini menjadi legitimasi bagi aktivitas yang merusak hutan, mengubah bentang alam, dan menurunkan kemampuan tanah menyerap air.
Akibatnya terlihat jelas hari ini. Ketika hujan turun deras, wilayah yang kehilangan tutupan hutan dan ruang resapan air tidak mampu menahan aliran air. Tanah mudah longsor, sungai meluap, dan banjir bandang terjadi dalam skala lebih besar daripada sebelumnya. Ini bukan bencana “tiba-tiba”, tetapi konsekuensi dari proses panjang yang diabaikan—bahkan didorong oleh kebijakan yang keliru.
Sistem Kapitalisme: Akar Kerusakan dan Kongkalikong Kekuasaan
Sikap penguasa dalam menjadikan alam sebagai komoditas wajar saja muncul dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme. Sistem ini memisahkan nilai moral dan ketuhanan dari tata kelola negara, serta menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai pengendali arah kebijakan.
Dalam sistem seperti ini, relasi penguasa dan pemodal berubah menjadi hubungan saling menguntungkan. Atas nama “pembangunan”, mereka mendapat legitimasi untuk menjarah hak milik rakyat—tanah, ruang hidup, sumber daya alam, bahkan keselamatan ekologis. Rakyat hanya menjadi objek, sementara keuntungan berputar di lingkaran sempit para pemilik modal dan elit politik.
Kerusakan lingkungan bukanlah penyimpangan, tetapi konsekuensi struktural dari sistem yang berorientasi profit. Ketika negara menjadi fasilitator kepentingan pemodal, lahirlah kebijakan yang mengabaikan keadilan sosial, menyingkirkan rakyat kecil, dan merusak lingkungan.
Maka tak heran penguasa cenderung zalim—bukan hanya karena karakter personal, tetapi karena sistem yang memungkinkan dan mengarahkan mereka demikian. Selama struktur ini dipertahankan, praktik kongkalikong akan berulang, kerusakan alam meningkat, dan bencana terus menghantam rakyat.
Musibah Sumatra: Cermin Buram Sistem yang Rusak
Musibah banjir dan longsor di Sumatra menunjukkan betapa berbahayanya perusakan lingkungan, terutama akibat pembukaan hutan besar-besaran tanpa mempertimbangkan daya dukung alam. Ketika hutan ditebang, tanah digali tanpa kontrol, dan ruang resapan air digantikan oleh konsesi raksasa, bencana tinggal menunggu waktu—dan kini waktunya telah tiba.
Kerusakan ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi buah dari sistem yang cacat sejak akar. Dalam kapitalisme, kebijakan sering lahir bukan untuk melindungi rakyat dan lingkungan, tetapi untuk mengakomodasi pemilik modal. Penguasa dan pengusaha bersekutu atas nama pembangunan, sementara rakyat menanggung risiko dan kehilangan: rumah, lahan, rasa aman, dan masa depan.
Bencana yang berulang menunjukkan kerusakan ganda: pada alam dan pada tata kelola kehidupan. Selama pengelolaan sumber daya alam berlandaskan orientasi profit, kerusakan akan terus terjadi dan membesar.
Perubahan yang dibutuhkan bukan perbaikan teknis, tetapi perubahan paradigma dan sistem—dari orientasi keuntungan menuju orientasi amanah, keadilan, dan keberlanjutan.
Islam sebagai Solusi Sistemik Pengelolaan Lingkungan
Al-Qur’an menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat ulah manusia. Peringatan ini bukan hanya pesan moral, tetapi panduan ilahi untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Menjaga lingkungan adalah bagian dari keimanan, dan larangan membuat kerusakan (fasad) merupakan prinsip utama dalam Islam.
Islam tidak sekadar memberikan ajaran moral, tetapi juga sistem pengaturan melalui negara. Dalam pemerintahan Islam, pengelolaan alam wajib mengikuti hukum Allah. Negara berkewajiban menata hutan dan DAS, mengatur pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan semuanya berjalan tanpa merusak atau menzalimi rakyat.
Negara Islam tidak hanya fokus pada penanggulangan bencana, tetapi mengutamakan pencegahan berdasarkan kajian ilmiah para ahli. Setiap kebijakan—dari pembukaan lahan hingga pembangunan infrastruktur—harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem.
Khalifah sebagai pemegang amanah kekuasaan akan mengambil kebijakan yang menghindarkan umat dari bahaya (dharar). Prinsip kemaslahatan umum menjadi fondasi keputusan. Tata ruang disusun komprehensif, berdasarkan fungsi alami wilayah: mana hutan lindung, mana permukiman, mana kawasan industri, dan mana yang harus dilindungi secara ketat.
Islam tidak hanya mengkritik kerusakan, tetapi menyediakan solusi sistemik untuk harmonisasi manusia dan alam. Ketika syariat diterapkan secara menyeluruh, bumi dapat dipulihkan, dan rakyat hidup lebih aman, layak, dan sejahtera. (*)