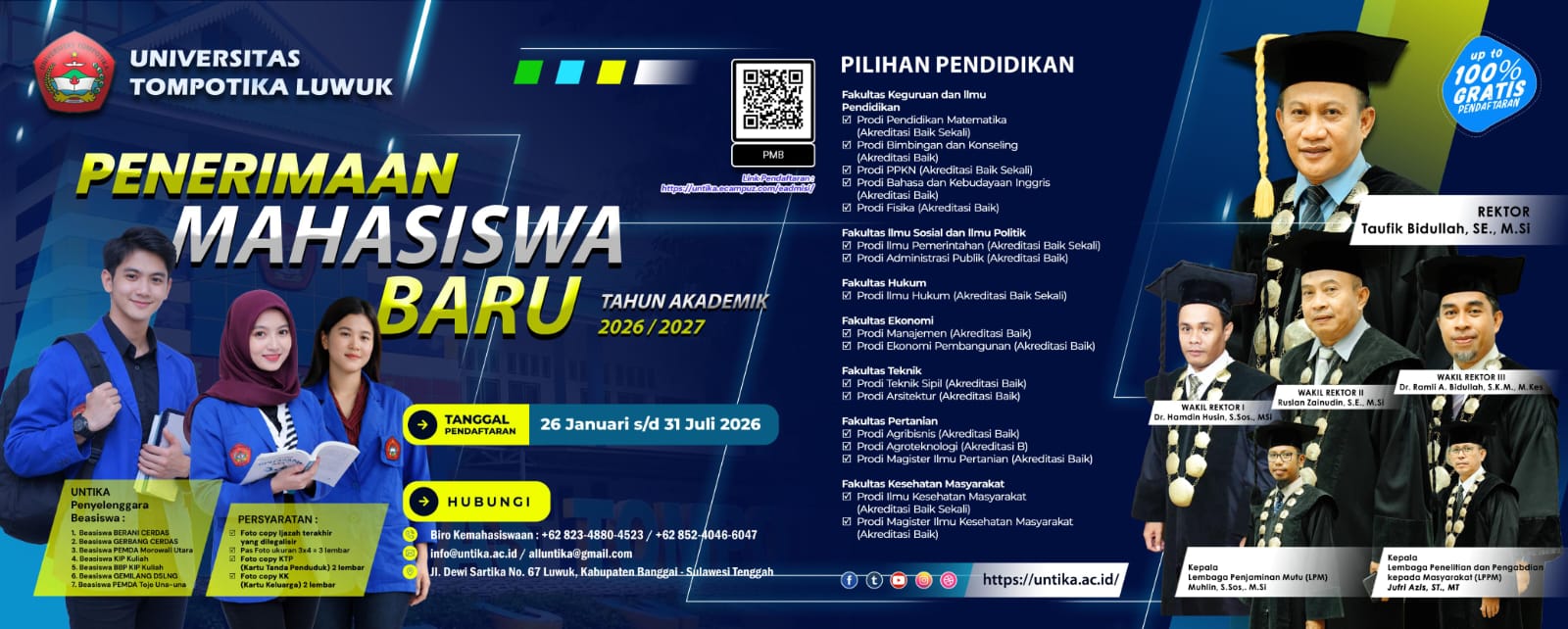Oleh: Hajir (Sang Pemain Takraw)
Sebagai penulis, objektivitas adalah syarat mutlak. Apalagi ketika memilih metode serta menentukan objek analisis. Dalam tulisan yang disoroti ini, penulis di salah satu media menggunakan metode studi komparasi secara deduktif, yaitu membandingkan objek yang bersifat umum dengan objek khusus di Kabupaten Banggai. Namun, pendekatan tersebut justru menghadirkan kecacatan logika yang cukup mendasar.
1. Pembangunan Jalan Lumpoknyo–Pasar Tua dan Kerangka Kinerja Makro Daerah
Dalam narasinya, penulis mensimulasikan manfaat produktivitas apabila jalan Lumpoknyo–Pasar Tua dibangun. Namun perlu dipahami, program prioritas dalam APBD TA 2026 dirancang agar selaras dengan KEM dan PPKF, sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2025 yang merujuk pada berbagai regulasi, mulai dari Pasal 18 UUD 1945, UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, hingga panduan KEM–PPKF Kementerian Keuangan.
Semua kerangka ini menegaskan bahwa pembangunan daerah harus diarahkan pada pencapaian Kinerja Ekonomi Makro Daerah, yaitu indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan diselaraskan dengan RPJMN, RKP, serta KEM–PPKF.
Target kinerja tahun 2026, misalnya:
Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,92% menjadi 5%.
Kemiskinan turun dari 6% menjadi 5%.
Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,11% menjadi 3%.
Rasio Gini turun dari 0,360 menjadi 0,300.
Pertanyaannya:
Bagaimana proyek jalan lingkar dan pembangunan RSUD 7 lantai dikaitkan dengan pencapaian IKU tersebut? PPAS yang menjadi bagian tak terpisahkan dari KUA justru mengikat pemerintah daerah pada kerangka kinerja makro, bukan pada proyek yang manfaatnya tidak terukur secara langsung terhadap indikator-indikator tersebut.
Berapa persen kemiskinan dapat turun di tahun 2026 jika jalan itu dibangun? Terlebih, pembangunan jalan tersebut adalah proyek multi years yang baru memberi dampak di 2028.
Menurut saya, penulis media tersebut mestinya tetap objektif dalam membangun argumentasi.
2. Tentang RSUD 7 Lantai: Substansi Pelayanan vs Infrastruktur Fisik
Narasi media atas pandangan fraksi yang disorot penulis menunjukkan adanya mitigasi risiko, terutama terhadap bencana. Namun substansi pelayanan kesehatan tidak pernah berdiri pada tinggi gedung, melainkan pada kualitas pelayanan.
Secara universal, kualitas pelayanan kesehatan memiliki lima dimensi:
Tangibles (fasilitas fisik),
Reliability,
Responsiveness,
Assurance,
Empathy.
Aktivis tersebut seharusnya memahami bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berorientasi pada lima dimensi ini. Jika tujuan utamanya peningkatan kualitas pelayanan, maka tidak perlu membangun RSUD berlantai 7. Gedung 3 lantai pun cukup, dan pembangunan selanjutnya bisa bertahap di area kosong lainnya. Pendekatan ini lebih efisien dan selaras dengan mitigasi darurat.
3. Substansi Cacat Logika: Kritik Kosong dan Perbandingan yang Keliru
Tulisan yang mengangkat pembangunan masa lampau dengan lokasi berbeda harus sangat hati-hati. Studi komparasi menuntut kesamaan objek dan subjek—baik sistem politik, ekonomi, maupun demokrasi.
Mencomot contoh seperti Jalan Inca di Amerika Selatan jelas tidak relevan. Pada masa Inca, sistem politik berbentuk kekaisaran yang seluruhnya bergantung pada keputusan kaisar. Sementara Indonesia, khususnya daerah seperti Banggai, berjalan dalam sistem perencanaan berjenjang: RPJMN → RKP → RPJMD → RKPD. Seluruh pembangunan daerah tunduk pada SPPN dan IKU.
Pembangunan daerah bukan tentang monumen atau piagam, tetapi peningkatan pelayanan.
Dukungan terhadap pembangunan jalan Pasar Tua–Lumpoknyo tentu sah, namun harus disertai kehati-hatian. Apalagi ketika kondisi keuangan daerah terbatas dan izin teknis dari PUPR belum sepenuhnya lengkap.
Hal yang sama terjadi pada rencana RSUD 7 lantai. Untuk apa membangun gedung sebesar itu jika substansi pelayanan kesehatan yang mendesak adalah penambahan ruang ber-ventilator? Dengan anggaran Rp200 miliar di 2025, kebutuhan mendesak seperti ini justru bisa diselesaikan pada triwulan pertama 2026, ketimbang menunggu RS 7 lantai rampung pada 2029.
Lebih lanjut, dari total belanja PUPR Rp303 miliar, sekitar 62% adalah pembangunan gedung kantor, termasuk RSUD 7 lantai. Narasi fiskal mestinya proporsional. Pembangunan jalan pendukung ketahanan pangan di pertanian dan kelautan justru lebih krusial dan harus didukung.
Inilah yang saya maksud dengan cacat logika — dan itu sangat berbahaya jika terus diulang dalam wacana publik. (*)