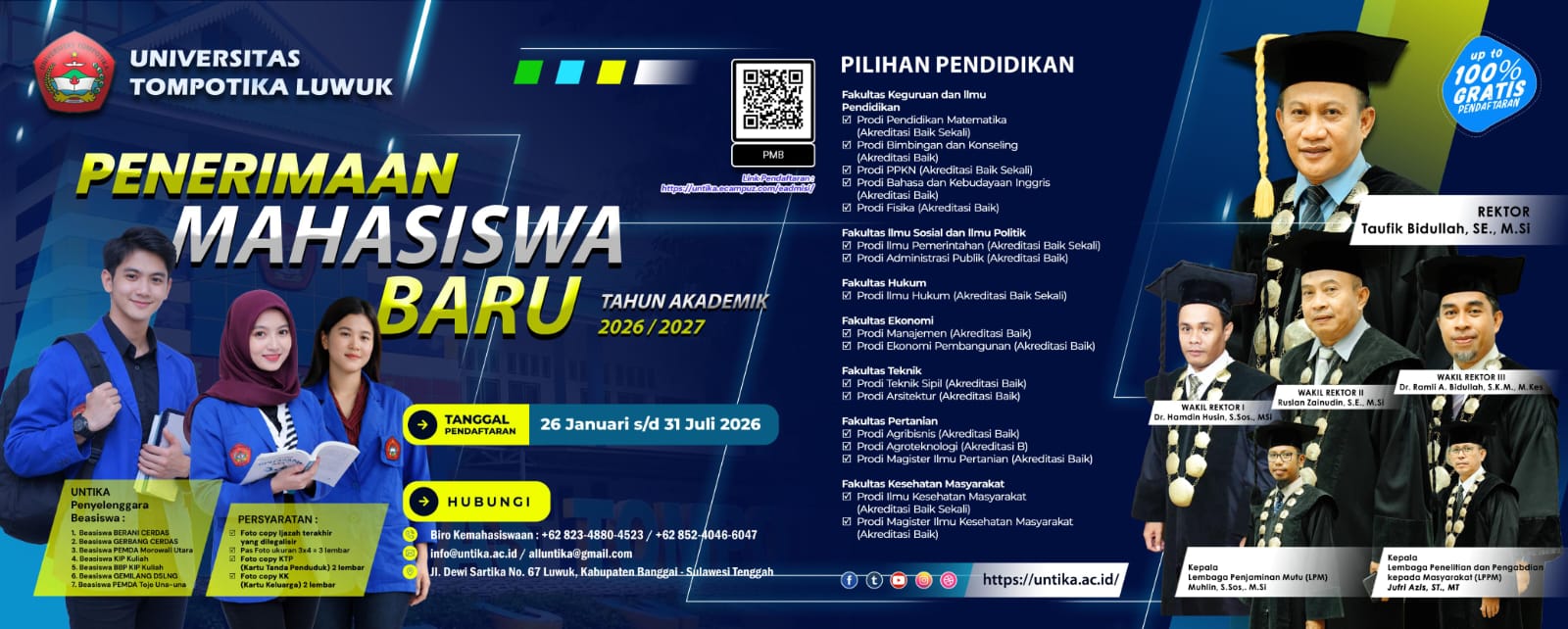Oleh: Suryani M. Sy. Zubair, SE
Pernikahan merupakan ikatan yang agung dan sarat makna. Namun realitas masa kini menunjukkan bahwa ikatan yang seharusnya kokoh tersebut kian rapuh, bahkan banyak yang berakhir di meja perceraian. Setiap tahun, grafik perceraian terus meningkat—menunjukkan bahwa banyak pasangan mampu memulai kehidupan bersama, tetapi tidak semua sanggup menapaki perjalanan panjang hingga akhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 349.608 kasus perceraian di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Tengah, angkanya mencapai 3.862 kasus, dengan sebaran: Banggai Kepulauan (-), Banggai (558), Morowali (392), Poso (173), Donggala (475), Toli-Toli (326), Buol (190), Parigi Moutong (509), Tojo Una-Una (257), Sigi (-), Morowali Utara (-), Kota Palu (773), dan Banggai Laut (209) dengan jumlah pernikahan 300.
(Sulteng.go.id, 27/02/2025)
Kenaikan perceraian terjadi di semua kelompok usia—mulai dari pasangan muda, pasangan yang telah puluhan tahun menikah, hingga fenomena grey divorce pada usia lanjut. Jika ditelusuri penyebabnya, pertengkaran yang terus berulang menjadi faktor terbesar, yakni 251.125 kasus atau 63% dari total perceraian tahun 2024. Masalah ekonomi menyusul dengan 100.198 kasus, yang menunjukkan rapuhnya ketahanan finansial keluarga. Selain itu, terdapat 7.243 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan yang besar namun kerap tersembunyi di balik angka statistik.
(CNBC Indonesia, 26/10/2025)
Fenomena ini bukan semata-mata masalah internal rumah tangga, tetapi mencerminkan struktur sosial yang melemah. Banyak keluarga runtuh karena persoalan yang sebenarnya bisa dikelola: konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, kekerasan, perselingkuhan, kecanduan judi online, hingga lemahnya karakter dan kesiapan individu.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memahami esensi dan tanggung jawab pernikahan. Mereka memasuki bahtera rumah tangga dengan harapan indah, tetapi tanpa kesiapan mental, kemampuan berkomunikasi, serta kesadaran bahwa pernikahan adalah proses bertumbuh bersama, bukan sekadar tempat mencari kenyamanan.
Tanpa kedewasaan emosional, kemampuan menyelesaikan masalah, dan komitmen saling menghormati, pernikahan mudah goyah. Cinta saja tidak cukup; ia membutuhkan ilmu, pemahaman, dan kedisiplinan dalam menjalankan peran masing-masing.
Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah mitsaqan ghalizha—sebuah perjanjian yang sangat kuat dan berat. Ia bukan hanya hubungan sosial, tetapi amanah ibadah yang dijalankan dengan penuh ketakwaan, demi menjaga kehormatan dan mewujudkan kedamaian keluarga. Namun ketika pernikahan dipandang sekadar hubungan pribadi atau sekadar tempat menyalurkan keinginan, maka sedikit gesekan saja bisa menjadi alasan untuk berpisah.
Sistem kapitalisme-sekuler yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan materi turut melemahkan ikatan keluarga. Relasi dinilai dari seberapa besar manfaat yang diperoleh, bukan sebagai amanah untuk membangun rumah tangga penuh kasih sayang. Masalah ekonomi yang sering menjadi pemicu perceraian pun memperlihatkan kegagalan sistem ini dalam menyejahterakan rakyat. Kekayaan hanya berputar di kalangan elit, sementara rakyat kecil menghadapi pajak tinggi, biaya hidup mahal, dan minimnya perlindungan sosial.
Sekularisme juga menarik agama dari ruang publik—dari pendidikan, media, hingga kebijakan negara. Generasi tumbuh dengan pola pikir yang serba bebas: bebas memilih pasangan, bebas menikah, dan bebas bercerai. Sementara itu, perempuan didorong meninggalkan peran utamanya sebagai pendidik generasi dan dijadikan tenaga kerja murah, sehingga tekanan peran ganda mendorong sebagian memilih perceraian sebagai jalan “pembebasan”.
Solusi Menurut Islam
Islam memandang bahwa problem perceraian tidak cukup diselesaikan lewat bimbingan konseling semata. Ia memerlukan perubahan menyeluruh—mulai dari individu, masyarakat, hingga negara.
Ketahanan keluarga dalam pandangan Islam bertumpu pada tiga kekuatan:
Kepribadian Islam yang kuat pada setiap individu.
Lingkungan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Islam.
Negara yang menerapkan sistem politik, sosial, dan ekonomi Islam untuk melindungi rakyatnya.
Pendidikan Islam menjadi fondasi pembentukan syakhshiyah islamiyah sejak dini, agar individu tumbuh dengan pola pikir dan perilaku berlandaskan akidah. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pembentuk keimanan, ketakwaan, dan rasa tanggung jawab kepada Allah.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak.”
(HR. Bukhari)
Dengan pendidikan seperti ini, laki-laki dipersiapkan sebagai qawwam (pemimpin keluarga), sementara perempuan sebagai ummun wa rabbatul bait (pendidik generasi dan penjaga rumah tangga). Pernikahan dipandang sebagai ibadah, sumber ketenteraman, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.”
(QS. Ar-Rum: 21)
Masyarakat yang menjadikan syariat Islam sebagai standar kehidupan akan menjaga interaksi sosial yang sehat dan menjauh dari kemaksiatan yang merusak keluarga. Sistem ekonomi Islam pun memastikan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat, menyediakan lapangan kerja, dan menjaga harga tetap terjangkau. Dengan demikian, suami tidak tertekan secara finansial, istri tidak terbebani peran berlebihan, dan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang stabil.
Ketika Islam diterapkan secara menyeluruh (kaffah), keluarga akan berdiri kokoh, dan angka perceraian yang disebabkan faktor sistemik dapat ditekan secara signifikan. (*)